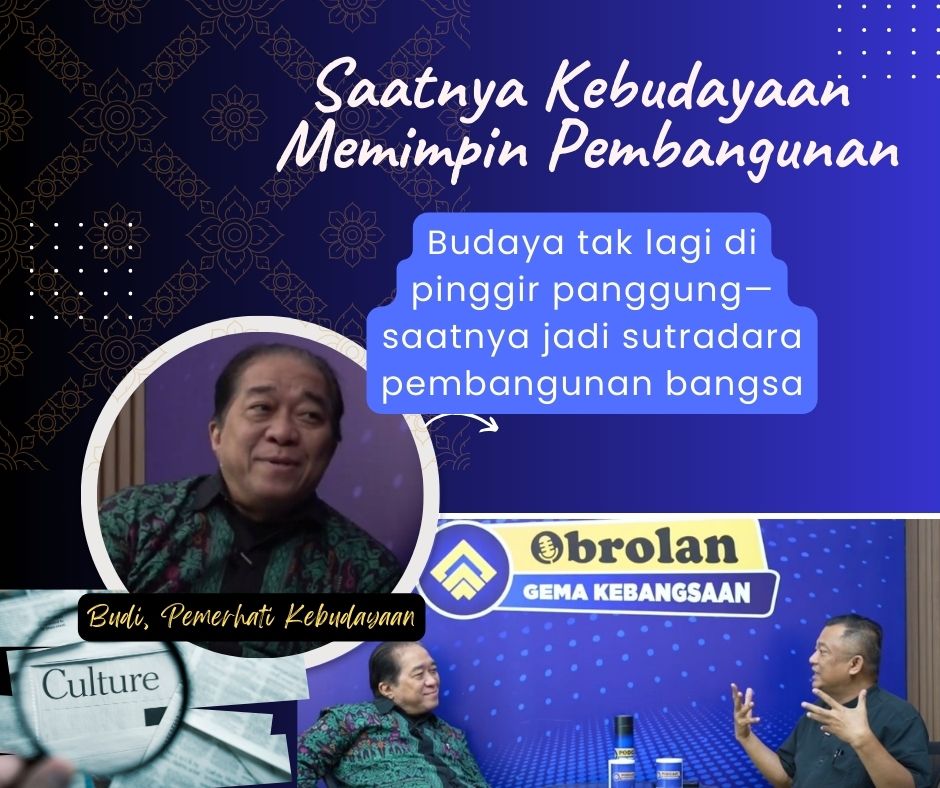
Di tengah persaingan global, Indonesia masih sibuk memperdebatkan arah pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Padahal, ada satu modal yang lebih abadi, nyaris tak terbatas, dan sudah terbukti menjadi mesin ekonomi dunia: kebudayaan.
Hal ini ditegaskan oleh kawan Budi, pemerhati kebudayaan, dalam podcast Obrolan Gema Kebangsaan bersama host Joko Kanigoro di kanal YouTube Gema TV. Menurutnya, Indonesia terlalu lama menempatkan budaya sebagai “hiasan seremonial” atau sekadar pelengkap acara kenegaraan, padahal di balik itu tersimpan peluang ekonomi raksasa.
Belajar dari Korea Selatan: K-Pop sebagai Mesin Devisa
Korea Selatan hanyalah contoh paling nyata. Negara yang dulu bergantung pada industri baja itu kini menjadi salah satu pusat budaya dunia. K-Pop, drama Korea, hingga gaya hidup ala Seoul menjelma sebagai ekspor strategis yang menembus pasar global. Pemerintah mereka tidak ragu menggelontorkan dana, bahkan mensubsidi artis agar bisa tampil di panggung dunia. Hasilnya? BTS dan Blackpink bukan hanya ikon hiburan, tetapi juga mesin devisa yang menyumbang miliaran dolar.
Dalam obrolan itu, kawan Budi menekankan bahwa dukungan negara terhadap ekosistem budaya di Korea begitu konkret. Mulai dari subsidi konser hingga kebijakan royalti yang jelas, semua diarahkan agar industri kreatif menjadi sumber kebanggaan sekaligus pemasukan.
Jepang: Etos Kerja dari Budaya
Sementara Jepang menunjukkan contoh lain. Negeri Sakura tidak hanya menjual animasi, kuliner, atau fesyen. Lebih dari itu, Jepang berhasil menanamkan etos kerja sebagai warisan budaya. Disiplin, dedikasi, dan penghormatan pada tradisi menjadi energi utama dalam pembangunan teknologi dan industri.
Budaya di Jepang tidak dibekukan sebagai artefak masa lalu, melainkan dihidupkan sebagai nilai yang membentuk perilaku masyarakat modern. Di sinilah letak kekuatan: budaya menjadi fondasi ekonomi sekaligus moral bangsa.
Indonesia: Kaya Warisan, Minim Arah
Indonesia memiliki ribuan bentuk budaya, dari musik tradisi, tarian, manuskrip, hingga kuliner. Namun, seperti dikatakan kawan Budi, “kebudayaan kita masih dijadikan objek, bukan subjek.” Artinya, budaya sering dimobilisasi untuk kepentingan politik jangka pendek, bukan dikelola sebagai aset nasional jangka panjang.
Lebih ironis lagi, alokasi anggaran kebudayaan masih sangat kecil. Padahal, dari sektor musik saja, potensi devisa sangat besar. Bayangkan jika band atau musisi Indonesia bisa mendapat dukungan negara untuk tampil di dunia internasional seperti halnya BTS.
“Budaya itu produk kemanusiaan yang paling independen. Tidak bergantung pada politik, tidak bergantung pada ekonomi. Justru politik dan ekonomi bisa runtuh, tapi budaya akan tetap hidup,” tegas kawan Budi dalam dialog itu.
Saatnya Politik Kebudayaan Jadi Arus Utama
Indonesia perlu segera menggeser paradigma. Politik kebudayaan tidak boleh berhenti pada seremonial pakaian adat di hari kemerdekaan. Ia harus menjadi strategi besar, dengan tujuan menjadikan budaya sebagai pilar pembangunan ekonomi, identitas nasional, sekaligus daya saing global.
Langkah konkret bisa dimulai dengan:
Meningkatkan anggaran kebudayaan secara signifikan, bukan sekadar 1% dari APBN.
Memberikan ruang bagi seniman dan budayawan dalam perumusan kebijakan, bukan hanya birokrat.
Membangun ekosistem kreatif yang melibatkan UMKM, teknologi digital, dan pendidikan.
Mengarusutamakan kebudayaan dalam diplomasi luar negeri, seperti yang dilakukan Korea dengan K-Pop dan Jepang dengan pop culture-nya.
Saatnya Budaya Memimpin Pembangunan
Belajar dari Korea dan Jepang, jelas bahwa budaya bukan sekadar simbol. Ia adalah energi peradaban sekaligus komoditas strategis. Indonesia dengan segala keragamannya memiliki modal yang jauh lebih besar. Yang dibutuhkan hanya keberanian politik untuk menjadikannya prioritas.
Seperti pesan kawan Budi di akhir perbincangan: “Kalau politik dan ekonomi bisa goyah, budaya tetap berdiri. Saatnya budaya tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek utama pembangunan bangsa.”




